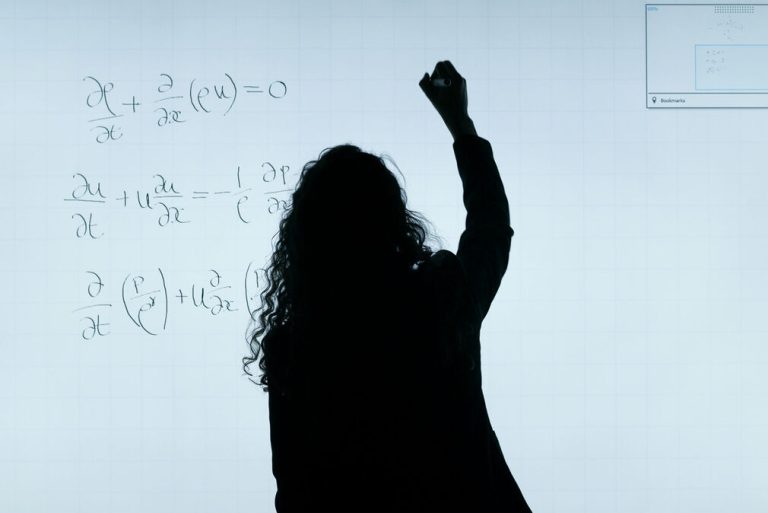TUGUJOGJA – Fenomena berkibarnya bendera One Piece di tengah ruang publik dan media sosial Indonesia telah memantik diskusi yang tidak biasa.
Di tengah sorotan publik dan kontroversi, seorang pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, angkat bicara dan membongkar tafsir semiotik di balik kegaduhan itu.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMY yang akrab disapa Fajarjun menanggapi fenomena ini secara mendalam dari perspektif semiotika.
Ia menyebutkan bahwa One Piece bukan sekadar tontonan hiburan, melainkan sebuah teks budaya populer yang kaya akan simbol, makna, dan pertarungan ideologis.
“One Piece adalah manga shōnen, yaitu manga yang menyasar remaja laki-laki sebagai pembaca utamanya. Namun di balik cerita petualangan dan fantasi, manga ini menyimpan pesan-pesan kuat tentang kerja keras, kemenangan, dan persahabatan,” ungkap Fajarjun saat ditemui pada Senin (4/8/2025).
Ia menekankan bahwa setiap karakter dalam One Piece memiliki fungsi representatif. Tokoh utama seperti Luffy merepresentasikan nilai-nilai luhur yang berhadapan dengan musuh-musuh yang bertindak sebagai oposisi biner dari nilai-nilai tersebut.
Dalam pertarungan itu, lanjutnya, terselip ideologi yang secara halus mengajak pembaca untuk memilih nilai mana yang layak diperjuangkan.
“Pertarungan itu bukan hanya adu kekuatan fisik, melainkan pertarungan ideologi. Manga seperti One Piece menjadi medan tempur pemaknaan dalam budaya populer,” ujarnya.
Simbol Bendera dan Kritik Sosial
Fajarjun menyebut elemen visual dalam One Piece, seperti desain karakter, pakaian, dan properti termasuk bendera bajak laut, sebagai bagian dari sistem tanda.
Ia menilai bahwa elemen-elemen ini menyampaikan pesan yang kuat melalui pilihan estetika yang tidak sekadar indah, melainkan sarat makna dan narasi budaya.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks semiotika lanjutan atau secondary signification, para karakter dan simbol dalam One Piece tidak berdiri netral.
Mereka memikul makna sosial-politik tertentu, menjadi jembatan menuju isu-isu yang lebih besar seperti keadilan, kebebasan, dan relasi kuasa.
“Saya merujuk pada penelitian Thomas Zoth (2011) dalam The Politics of One Piece: Political Critique in Oda’s Water Seven. Di sana terlihat jelas bagaimana One Piece mengangkat relasi antara individu dan negara. Isu keamanan nasional dibenturkan dengan hak individu, dan hasilnya adalah narasi yang menolak pengorbanan kebebasan demi stabilitas semu,” jelasnya.
Dengan landasan itu, Fajarjun menilai bahwa penggunaan bendera One Piece dalam demonstrasi simbolik di Indonesia memiliki lapisan makna yang dalam.
Ia tidak melihatnya sebagai sekadar tren atau candaan warganet, melainkan sebagai simbol identitas kelompok yang tengah melakukan resistensi terhadap situasi sosial dan politik tertentu.
“Dalam studi gerakan sosial, Alberto Melucci menegaskan pentingnya simbol yang menyatukan massa. Bendera, dalam hal ini, bukan hanya kain bergambar tengkorak, melainkan penanda eksistensi kelompok, alat perlawanan, dan bentuk ekspresi identitas,” katanya.
Menurut Fajarjun, fenomena ini menyajikan contoh konkret bagaimana budaya populer seperti anime dan manga bisa melebur ke dalam ranah aktivisme digital. Ia melihat bagaimana warganet menggunakan simbol One Piece, baik sebagai foto profil, status, maupun unggahan viral, untuk membentuk narasi alternatif, bahkan kritik sosial.
“Media sosial telah mengamplifikasi simbol ini. Bendera One Piece menyebar cepat, dan media massa kemudian memperbesar gaungnya. Namun celakanya, beberapa pejabat publik menanggapinya secara reaktif dan keliru. Pernyataan mereka justru memperparah citra pemerintah karena menunjukkan ketidakpahaman atas simbol dan narasi yang sedang dimainkan masyarakat,” tutup Fajarjun.